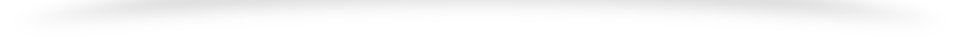oleh: Maimon Herawati
Shaufiqa Begum menimang anak bungsunya. Matanya menerawang. “Tidak ada perempuan yang mau melakukan ini [menjual dirinya],” tuturnya pada Nicolas Haque dari Al Jazeera. “Tapi, saya juga seorang Ibu. Saya harus memberi makan anak saya.” Dia menunduk, menatap tubuh tak berbaju bayinya. Di sampingnya, dua anak berusia kira-kira lima tahun dan dua tahun mendengar tuturan ibunya tanpa mengerti makna kalimat itu.
Shaufiqa dan tiga anaknya hidup dalam salah satu tenda di perbatasan Burma dan Bangladesh bersama ribuan Muslim Rohingya lainnya. Tenda-tenda dan rumah gubuk itu tanpa air bersih, tanpa listrik. Mereka tidak memiliki akses pada lembaga pendidikan dan rumah sakit. Anak-anak di sana menderita malnutrisi berat. Bantuan pangan dan kesehatan minim karena akses ke kamp Rohingya dijaga ketat pemerintah, militer, dan biarawan Budha. Pengamat internasional juga diusir.
Shaufiqa tidak sendiri. Gadis-gadis Rohingya –bahkan ada yang berusia empat belas tahun- menjual satu-satunya milik mereka demi kelangsungan hidup dalam kamp itu; tubuh mereka.
Brad Adams, pengamat hak asasi manusia berkata, “Rohingya adalah suku bangsa yang paling dilupakan di dunia.” Kejahatan kemanusiaan tidak terjadi akhir-kahir ini saja. Penindasan suku mayoritas Budha di Arakan (Atau Rakhine), provinsi bagian Barat Burma, terhadap Muslim Rohingya sudah berlangsung lama. Pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan fisik.
Saat tekanan itu tidak tertahan lagi, sebagian mereka melarikan diri ke Bangladesh dengan menaiki perahu-perahu. Enam jam menuju daerah mayoritas Muslim dan berharap bisa mendapatkan simpati dari saudara seiman, Rohingya mendapati kenyataan kehadiran mereka ditolak. Perahu mereka tidak sempat mendarat di pantai Bangladesh. Polisi dan tentara mengusir mereka kembali ke Burma.
Oli Ahmed, warga Bangladesh meyakini penolakan itu logis. “”Kami juga tidak cukup [pangan dan sandang]. Kami tidak ingin mereka di sini,” katanya pada Al Jazeera.
Mahfuz Salim, muslim Rohingya menerima kenyataan itu. “Polisi dan tentara Bangladesh menyerang kami. Mereka tidak ingin kami di sini.” Tapi, kembali ke Arakan, kampung halaman mereka pun sulit saat mereka diburu dan diserbu, saat mereka dipaksa hidup dalam ‘open air prison’, penjara alam terbuka, pelan-pelan menuju kepunahan entah karena tidak ada yang akan dimakan, ataupun karena penyakit karena buruknya kualitas hidup.
Kekerasan pada Rohingya
Eskalasi kekerasan baru-baru ini awalnya dipicu oleh pemerkosaan dan pembunuhan gadis Budha oleh pemuda Muslim pada Mei lalu. Pada 4 Juni, warga Budha mengamuk, menyerang bus di daerah Taungup karena percaya pemerkosa itu ada dalam bus. Sepuluh lelaki Muslim terbunuh dalam insiden itu.
Tiga lelaki Muslim kemudian ditahan bersangkutan dengan kasus pemerkosaan. Dua dikenai hukuman mati sedang yang satu lagi tewas dalam tahanan.
Tak lama setelah insiden bus, usai sholat Jumat, Muslim berkumpul di kota Maung Daw dan menyerang bangunan di sekitar mereka. Polisi menghentikan kerusuhan itu. Jam malam diberlakukan di Maung Daw, tapi kekerasan menjalar ke kota sekitar. Warga Budha menyerang desa-desa Muslim.
Saksi mata menjelaskan pada Guardian, dia melihat pemuda-pemuda Budha membakar kemaluan dan menusukkan besi pada anus lelaki-lelaki Muslim yang dikumpulkan di satu lokasi. Peneliti Amnesti Internasional, Benjamin Zawacki, menegaskan penyerangan akhir-akhir ini diarahkan pada warga keturunan Rohingya.”Sebagian penyerangan dilakukan militer Burma, sebagian warga Budha Arakan sedang militer menutup mata,” tuturnya pada Associated Press seperti dikutip Guardian. Amnesti juga mencatat penahanan ratusan Muslim Rohingya oleh militer yang, “melanggar hak asasi manusia, bebas dari diskriminasi karena agama.”
Pihak berwenang Burma tidak bisa dimintai komentar sampai saat tulisan ini diturunkan.
Bangsa Tanpa ‘Tanah Halaman’
Muslim Rohingya adalah minoritas terbesar di provinsi Arakan, Burma. Sejarah Muslim di Arakan mulai pada abad ketujuh ketika pedagang Muslim dari Arab menetap di sana. Muslim Rohingya sendiri merupakan keturunan Bengal yang sudah tinggal di Arakan sejak berabad lalu. Hampir mirip suku Tionghoa/India/Arab di Indonesia, barangkali. PBB memperkirakan ada sekitar 800 ribu Muslim Rohingya di Burma.
Menggunakan aturan yang dibuat pada 1982, Burma tidak mengakui Rohingya sebagai warga Burma, termasuk yang sudah menetap di Burma sejak masa pendudukan Inggris dulu. Gelombang kekerasan pada 1991, sebagian didukung Negara, memaksa 250 ribu Muslim Rohingya menyeberang ke Bangladesh, hidup dalam kamp minim fasilitas.
Nozir Hossain, 70, petani asal Maung Daw, tinggal di kamp ini sejak 2001. Pada Guardian dia berkisah bagaimana dia terusir dari rumahnya. “Warga Mogh [Budha] mengepung desa kami subuh itu. Nasaka [tentara perbatasan Burma] ada di belakang mereka. Mereka membakar rumah. Siapapun yang menghalangi mereka, mereka tebas, tusuk dan tembak. Dua anak lelaki saya mereka bunuh di depan mata saya. Ketika saya melindungi kepala dengan tangan, kapak nyaris memotong tangan saya. Saya terjatuh dan tergolek di atas genangan darah anak saya. Para pembunuh itu meninggalkan saya untuk mati kehabisan darah.”
Walaupun trauma itu demikian membekas, Nozir berharap bisa kembali ke tanahnya. “Tidak ada apa-apa bagi kami di sini,”katanya. Dia berharap pemerintah Burma akan adil dan memberikan kembali haknya. Saat dia pulang ke rumahnya pada 2005, dia dapati Mogh mendiami tanahnya. Karena itulah dia terpaksa kembali ke kamp.
Nozir menegaskan dua pemerintahan (Bangladesh dan Burma) ini salah menilai posisi Rohingya. “Burma mengatakan saya orang Bangladesh, padahal Arakan satu-satunya rumah saya. Bapak dan Kakek saya lahir di Arakan. Bangladesh mengatakan kami pendatang illegal. Padahal kami tidak datang ke Bangladesh mencari kerja. Kami ke sini menyelamatkan diri.”
Presiden Burma, Thein Sein, mengatakan ketegangan antar suku di Arakan bisa diselesaikan jika PBB mau menampung Muslim Rohingya atau Negara ketiga menerima mereka. Kepala UNHCR, Antonio Guterres menolak beban itu.
Foto Hoax di Jejaring Sosial
Duka Rohingya menjadi kabur karena banyaknya beredar foto-foto palsu di jejaring sosial media. Salah satu foto yang diklaim sebagai tindak kekerasan terhadap Rohingya adalah foto demonstran Tibet yang membakar dirinya di jalan. Sebagian warga dunia maya kehilangan minat untuk mengikuti berita Rohingya dengan alasan banyak kebohongan publik tentang penindasan itu, sementara tiap detik trauma baru mengguncang batin anak-anak Rohingya.
References: Guardian, Independent, BBC, Al Jazeera